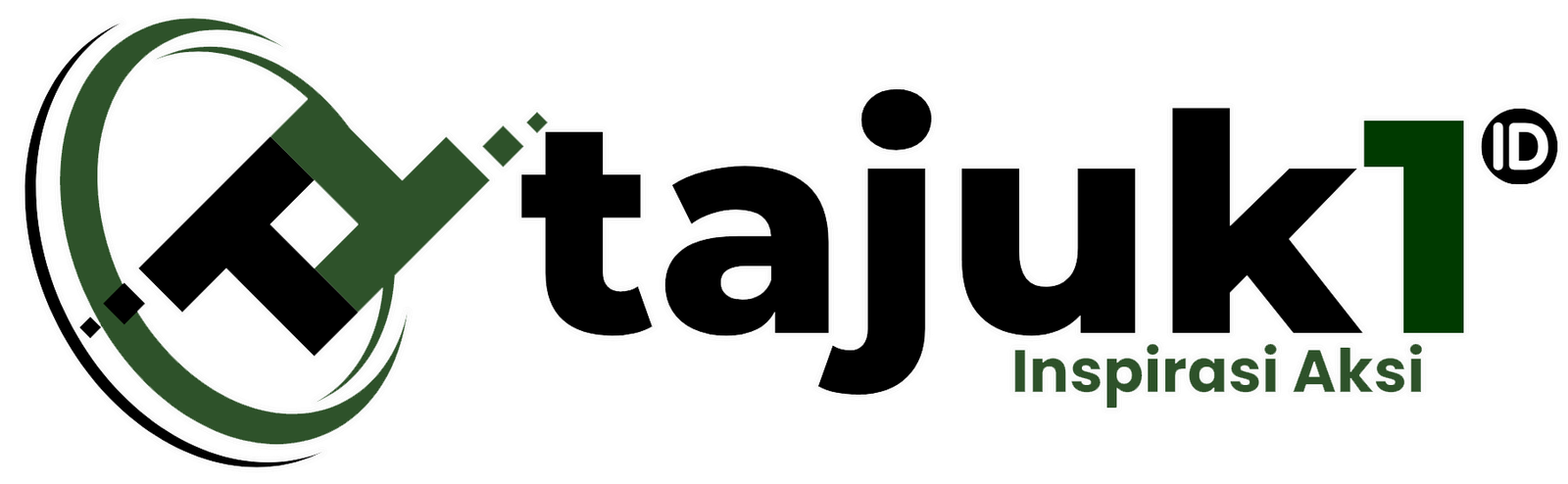Penulis: Faldi Puluhulawa (Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo)
TAJUK1.ID, Opini – Di tengah riuhnya jagat maya Gorontalo, sebuah flayer yang memuat seruan penolakan terhadap keberadaan waria mendadak viral. Gambar sederhana namun sarat pesan itu tersebar cepat melalui Insta Story, WhatsApp, hingga lini masa Facebook.
Sebagian mengamini, sebagian lagi bertanya, dan tidak sedikit yang memilih diam, barangkali karena takut salah bicara, atau karena memang belum tahu harus berpihak ke mana.
Sebagai anak daerah yang tumbuh dalam jejak-jejak budaya Gorontalo, saya tergugah untuk menulis ini bukan untuk membela satu pihak, tetapi untuk membuka ruang tafsir yang lebih luas: bagaimana sebenarnya masyarakat kita memahami keberagaman?
Dalam ranah kebudayaan Gorontalo, kita mengenal nilai-nilai hulondalo lipu, di mana kekerabatan, penghormatan terhadap sesama, dan konsep “modaati” (malu) dan “modudu” (takut kepada Tuhan) menjadi fondasi dalam bertindak.
Namun hari ini, kita dihadapkan pada realitas sosial baru yang memantik tafsir ulang terhadap nilai-nilai itu. Apakah penolakan terhadap waria adalah bentuk menjaga moralitas? Atau sebenarnya ia mencerminkan ketidaksiapan budaya dalam merangkul perbedaan?
Waria bukanlah fenomena baru di tanah ini. Dalam pasar-pasar, di salon-salon, bahkan dalam ruang-ruang hiburan, mereka telah lama hadir.
Yang baru justru adalah cara kita bersikap terhadap mereka—seakan dunia maya telah menjadi tempat di mana moralitas bisa diringkus menjadi flayer digital, tanpa ruang dialog dan pemahaman kontekstual.
Dalam tradisi lisan Gorontalo, kita diajarkan untuk tuliya to wawu, tulalo to dulamala—melihat dengan mata hati, mendengar dengan empati. Maka ketika flayer itu menyebar dengan narasi penolakan yang nyaris tanpa kompromi, yang kita lihat adalah gejala: masyarakat sedang gelisah.
Tapi gelisah bukan berarti benar. Gelisah bisa lahir dari ketidaktahuan, dari trauma, atau dari takut akan sesuatu yang belum dipahami.
Kita hidup dalam masyarakat majemuk, bahkan di Gorontalo yang tampak homogen. Di balik wajah adat dan agama yang kuat, ada individu-individu yang memikul identitas berbeda. Mereka tidak minta disanjung, mereka hanya ingin tidak ditolak.
Budaya bukan pagar besi, ia adalah taman yang bisa ditanami dengan ragam bunga. Bila ada satu bunga yang tumbuh berbeda, apakah lantas kita harus mencabutnya?
Apa yang viral di media sosial seharusnya menjadi momen reflektif, bukan justifikasi. Kita bisa tidak sepakat, tetapi menolak dengan cara membungkam adalah kegagalan memahami bahwa kemanusiaan itu tak pernah tunggal.
Waria adalah bagian dari masyarakat kita. Mereka punya nama, keluarga, dan cerita. Yang kita butuhkan adalah ruang diskusi, bukan penghakiman.
Jika kita benar-benar ingin menjaga nilai budaya Gorontalo, maka marilah kita mulai dari memahami bahwa tolitihu—rasa malu—tidak seharusnya diarahkan untuk menyembunyikan mereka yang berbeda, tetapi untuk menyadarkan bahwa menolak sesama tanpa dasar yang adil adalah bentuk kehilangan rasa hormat terhadap nilai itu sendiri.