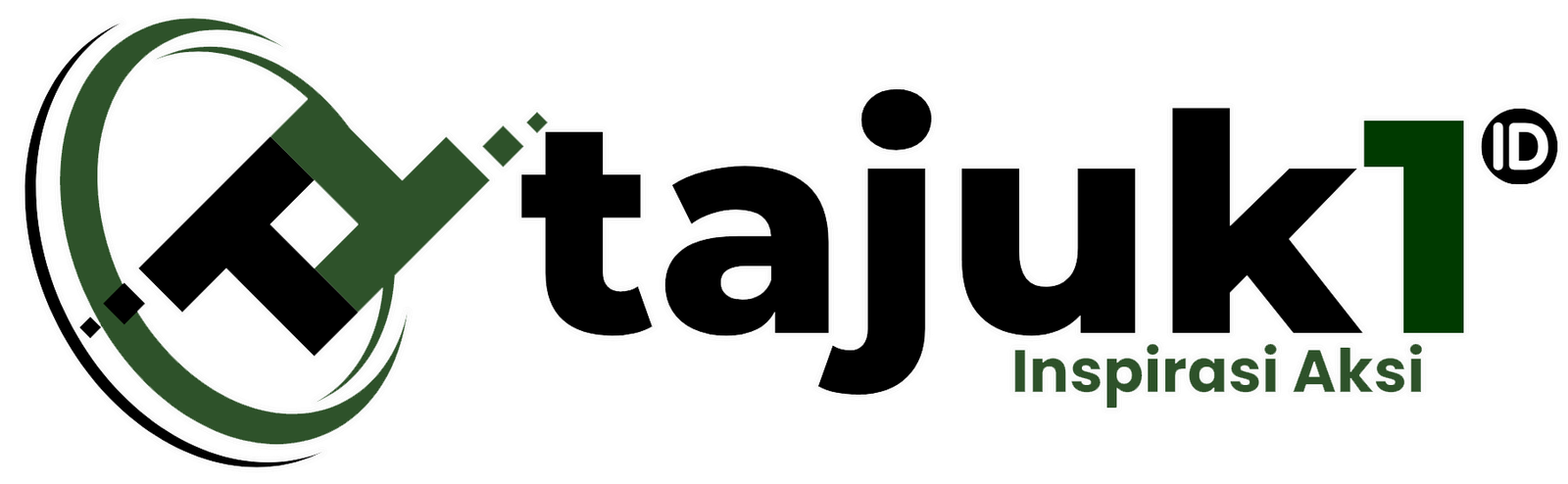Penulis : Mega Anastasya Diska Mokoginta
TAJU1.ID – Aku menulis cinta pertamaku di atas selembar kertas putih, dan di sana tertulis satu nama: Ayah.
Betapa aku bersyukur pernah digenggam oleh tangan itu tangan penuh kasih yang dulu menuntun langkah kecilku. Kini aku tumbuh dewasa, namun di hadapan Papa, aku tetaplah anak kecil yang rapuh dan manja.
Tulisan ini adalah upaya kecil untuk memutar waktu menyusuri kembali jejak perjalanan kami: aku dan Papa, sebutan lembut yang mengandung begitu banyak makna.
Dulu, setiap kali aku menangis dimarahi Mama karena kenakalanku atau diejek teman-teman soal tubuhku yang besar Papa selalu datang paling dulu.
Pelukannya jadi tempat berlindung dari dunia kecilku yang kadang terasa kejam. Dari sanalah aku belajar tentang keteguhan: bagaimana berdamai dengan luka, menertawakan cela, dan tumbuh dengan kepala tegak.
Papa pernah mengenalkanku pada lagu “Gajah” dari Tulus. Awalnya aku membencinya. Aku pikir, Papa ikut-ikutan mengejek seperti teman-teman lain. Tapi waktu, seperti biasa, menyingkap makna tersembunyi dari candanya.
Ternyata Gajah bukan ejekan, tapi doa. Simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Papa ingin aku tumbuh seperti itu teguh, lembut, dan cerdas.
Kini, jarak membentang di antara kami. Aku yang beranjak dewasa memilih berjalan ke luar rumah, mengejar mimpi yang dulu hanya diceritakan di meja makan.
Setiap kali aku pulang, kulihat Papa yang tak lagi muda. Kerutan di wajahnya menjadi puisi waktu, tubuhnya mulai renta, dan tangan yang dulu kuat kini sering letih.
Namun tawa itu… masih sama. Masih menjadi pelita yang menenangkan jiwaku menambal sepi, menyudahi pilu, dan memulihkan segala yang retak.
Dari Papa, aku belajar tentang cinta bukan yang berisik dan meledak-ledak, tapi yang tenang, sabar, dan tulus.
Cinta yang tidak banyak bicara, tapi selalu ada dalam bentuk paling sederhana: kerja keras, tanggung jawab, dan doa yang tak pernah selesai ia panjatkan.
Mama adalah perempuan beruntung yang bertemu dengan Papa lelaki yang memperjuangkan segalanya tanpa pamrih.
Dalam rumah kecil kami, Papa adalah raja tanpa mahkota, dan dengan cinta yang sama, ia menobatkan Mama, aku, dan Afika sebagai ratunya.
Kini aku mengerti, kasih sayang Papa bukan sekadar perasaan. Ia adalah filsafat kehidupan: bahwa cinta sejati tidak selalu terlihat, tidak selalu berbunyi.
Kadang ia hadir dalam diam, dalam kerja yang tak pernah diminta balas, dalam doa yang disembunyikan di balik senyum letih.
Menulis tentang Papa adalah menulis ulang masa kecil yang tak pernah pudar. Di antara ribuan kenangan, yang paling indah adalah satu hal yang tak pernah berubah: Papa, yang tak pernah lelah menanamkan kekuatan dan cinta di setiap langkah hidupku.