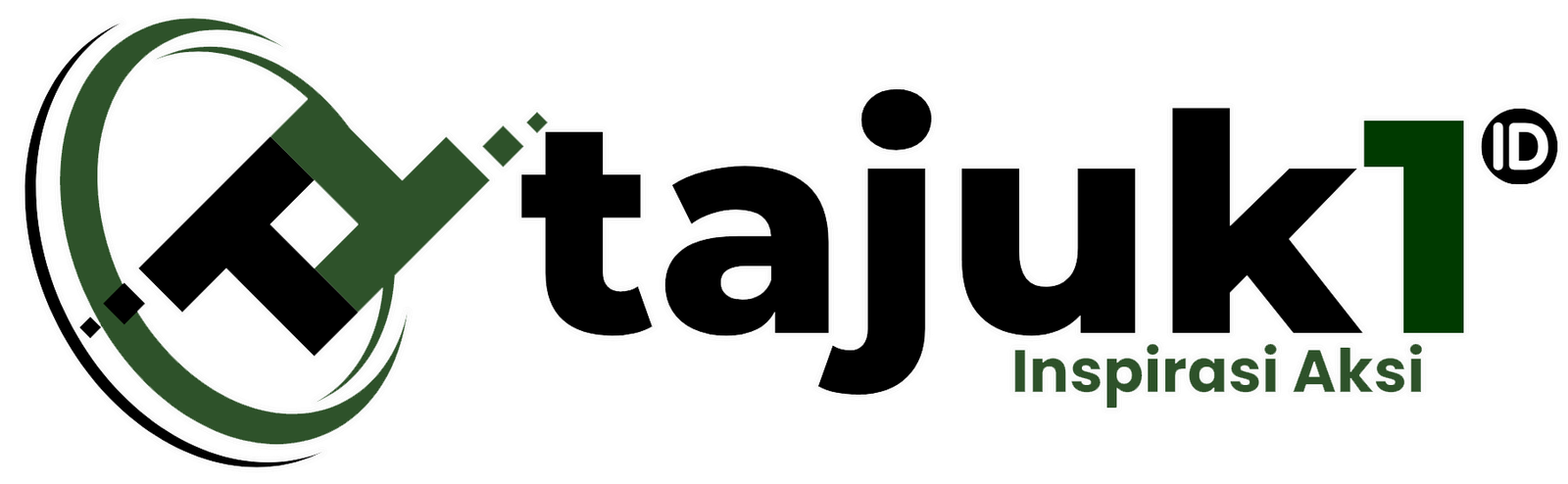TAJUK1.ID – Setiap musim penghujan tiba, Gorontalo kembali memasuki babak cerita yang berulang. Air sungai naik melampaui tebingnya, hamparan sawah berubah menjadi genangan luas, dan ruas jalan perlahan menjelma aliran lumpur kecoklatan. Banjir tidak lagi terasa sebagai kejadian luar biasa, melainkan seperti siklus yang datang tanpa jeda.
Pada saat bersamaan, di wilayah hulu, aktivitas yang berbeda berlangsung. Deru alat berat terus merayap ke lereng perbukitan, membuka lapisan tanah, menebangi vegetasi, dan membongkar batuan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan: mengejar kandungan emas yang dianggap menjanjikan keuntungan cepat.
Di tengah euforia ekonomi ekstraktif tersebut, Gorontalo kini berada di titik pertanyaan mendasar—berapa ongkos ekologis yang harus dibayar untuk setiap gram emas yang berhasil diangkat dari dalam bumi.
Hulu Tergerus, Hilir Menanggung Dampak
Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kawasan perbukitan dan hutan di Gorontalo meningkat signifikan. Di Pohuwato dan Boalemo, aktivitas pertambangan, baik skala industri maupun rakyat, terus merangsek masuk ke wilayah yang secara ekologis berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Situasi serupa juga terlihat di Bone Bolango, di mana pertambangan rakyat berkembang dengan pola berbeda, namun tetap memberi tekanan terhadap bentang alam hulu.
Secara geografis, Gorontalo berada dalam konfigurasi wilayah cekungan. Kondisi ini membuat aliran air dari hulu dengan cepat terkonsentrasi di dataran rendah. Ketika hujan deras turun, tidak adanya penahan alami seperti hutan menyebabkan limpasan air meningkat drastis dan memicu banjir.
Akademisi lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, Sri Sutarni Arifin, menegaskan bahwa pembangunan di daerah seperti Gorontalo semestinya bertumpu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Menurutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan seperti KLHS, RTRW, dan RDTR. Namun persoalan utama terletak pada implementasi yang belum konsisten.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan wilayah tidak dapat dilakukan secara parsial. Hulu dan hilir merupakan satu sistem ekologi yang saling terhubung.
Pembukaan lahan di lereng curam, menurutnya, memperbesar risiko longsor, mempercepat sedimentasi sungai, serta meningkatkan potensi luapan ketika curah hujan tinggi.
Sejumlah penelitian di kawasan tropis menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan sebesar 10–20 persen saja mampu meningkatkan puncak aliran sungai hingga 30–50 persen.
Konsekuensinya, banjir yang sebelumnya terjadi dalam siklus lima tahunan dapat berubah menjadi kejadian dua tahunan bahkan tahunan.
Sri menegaskan bahwa biaya ekologis dari kerusakan hutan jauh lebih mahal dibanding pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul atau normalisasi sungai.
Antara Moratorium dan Ekspansi
Dalam kondisi kerusakan yang semakin meluas, Sri menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan moratorium pertambangan, khususnya di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai yang memiliki fungsi vital.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data konsesi serta pengelolaan dana rehabilitasi lingkungan melalui skema escrow fund yang terpisah dari dana operasional perusahaan.
Tanpa kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian, menurutnya, Gorontalo berpotensi menghadapi beban ekologis jangka panjang yang jauh lebih besar dibanding manfaat ekonomi jangka pendek.
Daya Tarik Ekonomi Tambang
Di sisi lain, kehadiran tambang membawa narasi kesejahteraan yang sulit ditolak. Perputaran uang berlangsung cepat, dan dalam waktu singkat seorang pekerja tambang dapat memperoleh penghasilan setara setengah bulan pendapatan sektor lain.
Desa-desa yang sebelumnya sunyi berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi. Warung, bengkel, hingga jasa transportasi tumbuh mengikuti dinamika tambang.
Di Pohuwato, proyek berskala industri seperti Pani Gold Project menjadi simbol masuknya investasi besar. Bersamaan dengan itu, pertambangan tanpa izin juga berkembang di berbagai titik.
Perwakilan Japesda, Renal Husa, menyebut ketergantungan masyarakat terhadap tambang merupakan respons atas ketidakpastian ekonomi sebelumnya.
Ia mencontohkan kondisi di Duhiadaa dan Buntulia, di mana sedimentasi irigasi menyebabkan sawah gagal panen. Endapan lumpur bahkan telah mencapai kawasan pesisir, mengurangi populasi ikan dan menekan pendapatan nelayan.
Menurutnya, ketika sektor pertanian dan perikanan tidak lagi memberikan kepastian, masyarakat mencari alternatif penghidupan, dan tambang menjadi pilihan yang dianggap paling cepat.
Namun pilihan tersebut, katanya, justru berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.
Perubahan Struktur Sosial Desa
Peralihan dari sektor agraris menuju ekonomi ekstraktif tidak hanya mengubah jenis pekerjaan, tetapi juga menggeser struktur sosial masyarakat desa.
Ketika mayoritas warga bertani atau melaut, hubungan sosial cenderung berbasis solidaritas. Namun kehadiran tambang memunculkan kelompok baru yang memiliki akses modal dan teknologi.
Sebagian warga lain hanya menjadi buruh dengan posisi tawar rendah.
Ketimpangan ekonomi menjadi semakin terlihat. Sebagian masyarakat mengalami lonjakan pendapatan, sementara yang lain kehilangan lahan dan ruang hidup.
Orientasi sosial pun bergeser dari keberlanjutan jangka panjang menuju keuntungan instan. Generasi muda mulai meninggalkan pertanian karena dianggap tidak menjanjikan.
Situasi ini berpotensi memicu konflik sosial, baik antara masyarakat dan perusahaan maupun antar warga sendiri.
Kelompok Rentan yang Terpinggirkan
Renal juga menyoroti bahwa aktivitas tambang cenderung lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.
Perempuan yang sebelumnya terlibat dalam sektor pertanian kehilangan ruang produksi ketika lahan menyempit.
Kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, anak-anak, dan warga tanpa lahan menjadi pihak yang paling sulit beradaptasi ketika kualitas lingkungan menurun.
Tanpa tata kelola yang inklusif, aktivitas pertambangan berpotensi memperlebar ketimpangan sosial di tingkat desa.
Melemahnya Peran Adat
Pemerhati sejarah dan budaya Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai eksploitasi pertambangan yang masif saat ini tidak terlepas dari melemahnya sistem adat sebagai rambu pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, pemerintah belum optimal menghidupkan kembali mekanisme adat seperti Bandhayo Poboide yang dahulu berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan kolektif.
Ia menjelaskan bahwa prinsip adat “Tuwawu duluwo limo lo pohala’a” sejak lama menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Dalam pandangannya, jika prinsip adat tersebut ditegakkan, aktivitas pertambangan tidak akan berlangsung tanpa kontrol sosial.
Ali juga menyoroti adanya standar ganda dalam akses pengelolaan sumber daya, di mana investor relatif mudah memperoleh izin, sementara masyarakat lokal justru kerap dianggap ilegal.
Ia menilai penguatan kembali kerapatan adat penting agar pengelolaan sumber daya dapat mempertimbangkan aspek sosial, ekologis, dan kultural secara menyeluruh.
Menurutnya, tanpa pembatasan yang jelas, eksploitasi pertambangan berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat Gorontalo di masa depan.