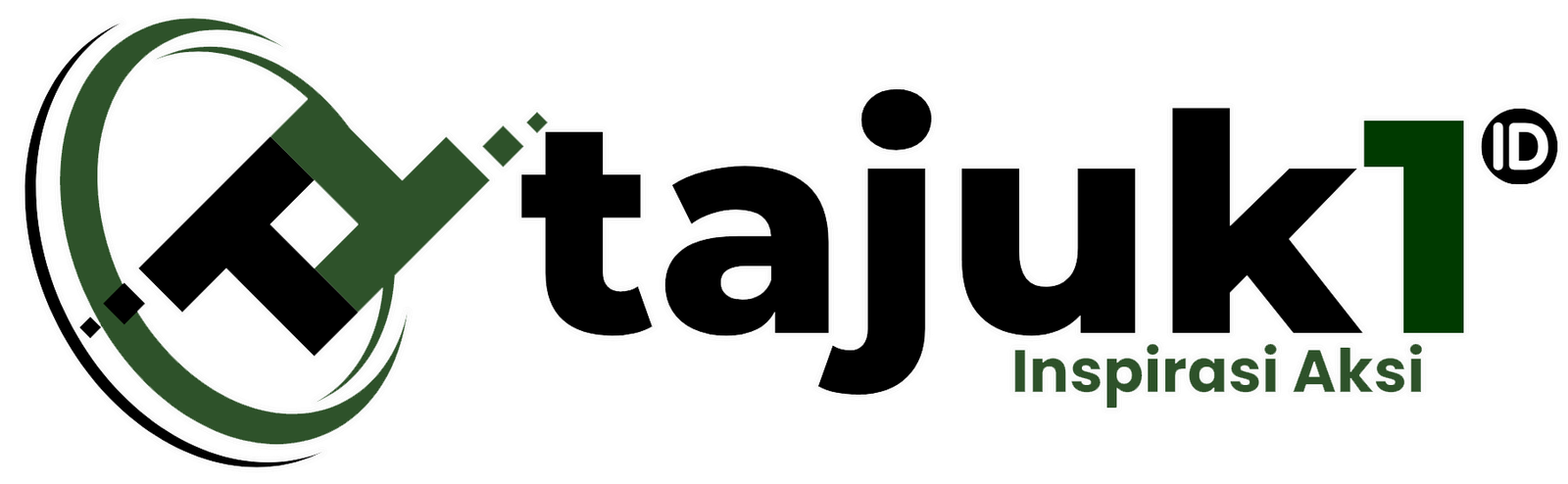Penulis : Khalifa Rido (Aktivis Gorontalo)
TAJUK1.ID – Ada ironi yang terlalu telanjang untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Ketika banjir bandang merobek Dusun Kapali, Desa Hulawa, dan menyisakan trauma serta kerugian warga, sebagian pihak justru sibuk merias diri dengan jargon kepedulian.
Tim YR tampil ke muka, mengusung narasi “normalisasi sungai”, seolah lupa atau pura-pura lupa bahwa sungai yang mereka keruk hari ini adalah sungai yang mereka rusak kemarin.
Apresiasi? Terlalu murah untuk diberikan pada tangan yang sama yang diduga kuat menggenggam sekop perusakan.
Sebab, sebelum alat berat menyingkirkan sedimen pascabanjir, ada jejak panjang aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang mengoyak daerah hulu, menggerus bantaran, dan menumpuk lumpur di alur sungai.
Banjir tidak jatuh dari langit sendirian; ia dilahirkan oleh keserakahan yang sistematis. Secara hukum, PETI bukan sekadar “kesalahan prosedural”. Ia adalah perbuatan melawan hukum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin.
Pasal 158 menyebutkan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara dan denda besar. Tidak ada ruang tafsir abu-abu di sana. Tambang tanpa izin adalah kejahatan, bukan kerja bakti.
Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi pidana dan perdata.
Kerusakan hulu, pendangkalan sungai, dan meningkatnya risiko banjir adalah bentuk kerusakan nyata, bukan opini emosional warga yang kebanjiran.
Maka, ketika Tim YR yang diketahui dibentuk oleh pelaku usaha pertambangan mengklaim normalisasi sungai sebagai “inisiatif kepedulian”, publik patut curiga.
Kepedulian macam apa yang datang setelah kehancuran? Kepedulian yang baru muncul ketika air bah sudah menelan rumah warga? Ini bukan empati ini kosmetika moral. Upaya menutup lubang dengan plester setelah tembok diruntuhkan.
Normalisasi sungai yang dilakukan pascabanjir, tanpa pengakuan kesalahan dan tanpa penegakan hukum terhadap aktivitas PETI, justru tidak dapat dibenarkan.
Ia berpotensi mengaburkan tanggung jawab pidana, bahkan memutihkan kejahatan dengan label kegiatan sosial. Seolah-olah pelaku boleh merusak lebih dulu, lalu menambal sedikit, dan berharap tepuk tangan publik menghapus dosa ekologis.
Di titik ini, aparat penegak hukum (APH) tidak boleh terpukau oleh panggung kepedulian dadakan.
Justru sebaliknya, inilah momentum untuk menarik benang merah: siapa yang menambang, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Banjir adalah alarm keras bahwa hukum selama ini terlalu sunyi.
Penyelidikan harus menyasar dugaan dalang PETI, menelusuri aliran aktivitas, dan menindak tegas para pelaku bukan sekadar memotret ekskavator yang sedang “berbuat baik”.
Apresiasi yang salah alamat hanya akan memperpanjang siklus rusak–tambal–rusak. Jika negara masih ingin disebut hadir, maka hukum harus ditegakkan tanpa tedeng aling-aling.
Sungai tidak butuh pencitraan ia butuh keadilan. Warga tidak butuh seremoni; mereka butuh jaminan bahwa bencana yang sama tidak akan diulang oleh tangan yang sama.